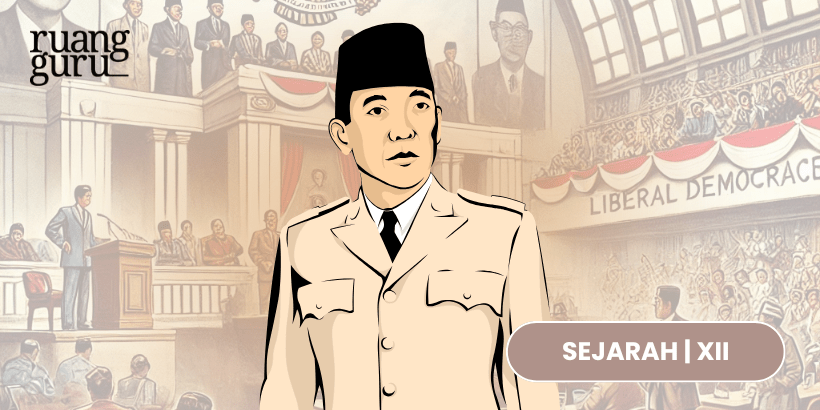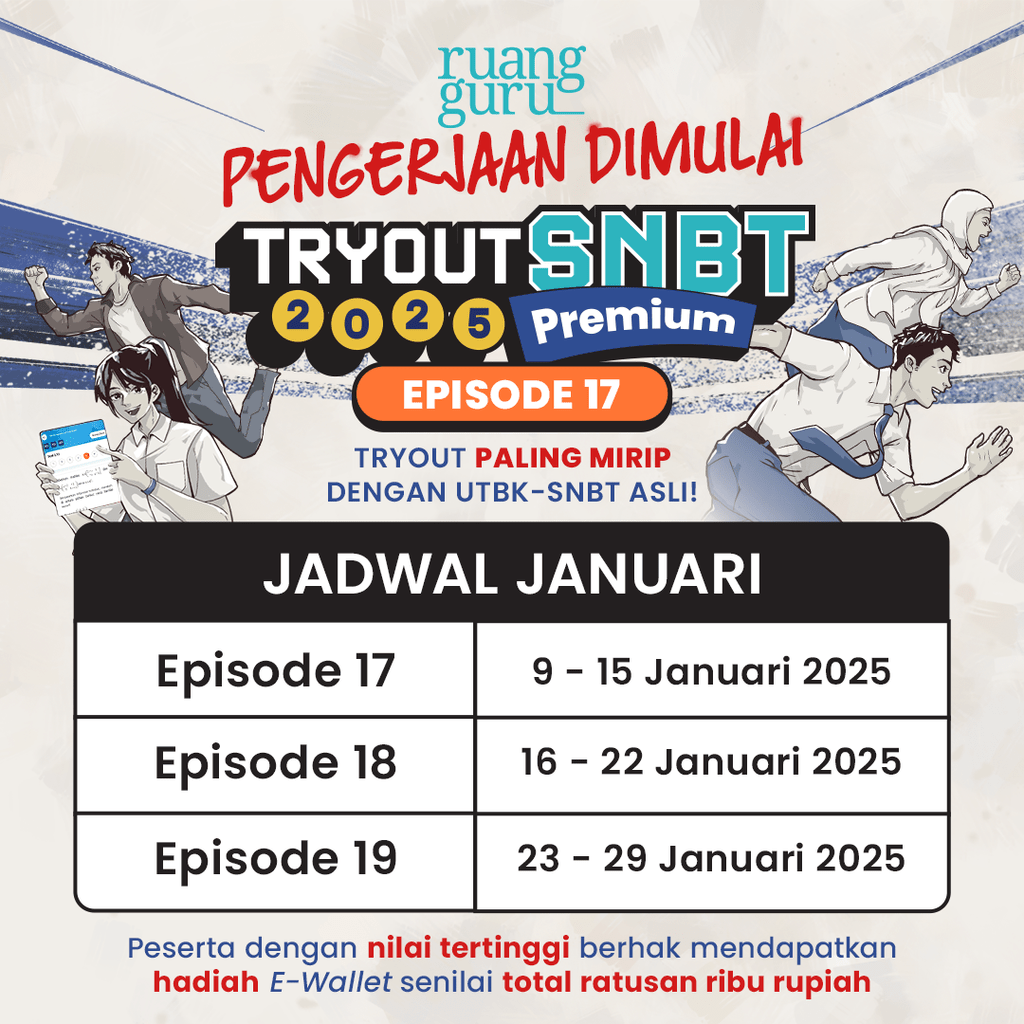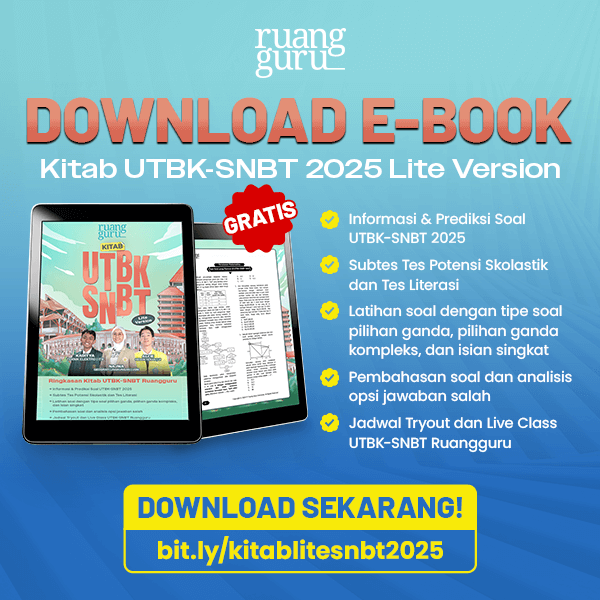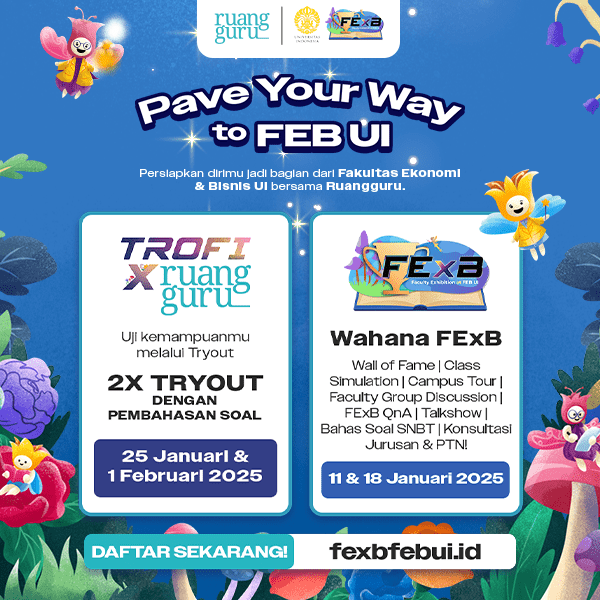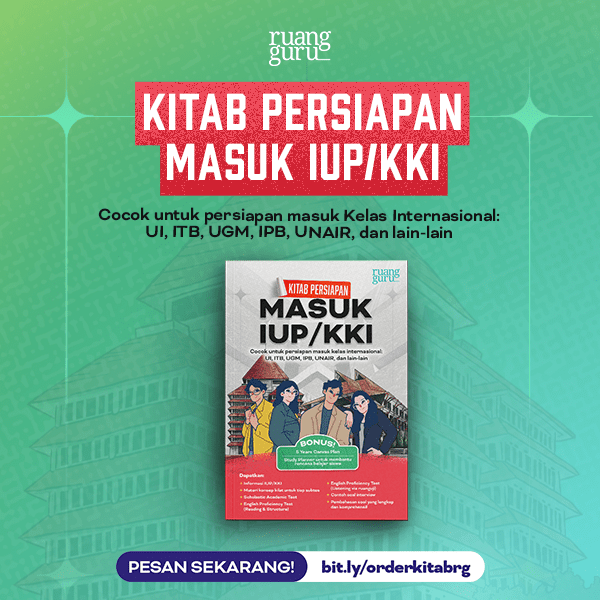#CeritaGuru: Polemik Dibalik Iklan Sekolah Gratis
Maraknya iklan sekolah gratis yang ditayangkan di media elektronika memang mengharukan. Iklan di-setting lebih pada dunia keseharian, yang melibatkan orang tua siswa dengan beragam profesi, antara lain tukang ojek dan sopir angkot. Iklan ini juga memberi pencerahan tentang profesi anak-anak di masa depan, tanpa memandang profesi orang tuanya. Iklan ini juga diakhiri dengan kalimat: “Sekolah bisa.”
 Ibu Ni Luh Putu Widiartini (Sumber: dok. pribadi)
Ibu Ni Luh Putu Widiartini (Sumber: dok. pribadi)
Siapa pun yang menyimak iklan itu akan larut dalam situasi emosional. Iklan sekolah gratis di layar kaca tersebut menyiratkan makna bahwa sekolah memang untuk semua. Tidak memandang anak orang kaya atau miskin, berasal dari kota atau desa, tak membedakan laki-laki atau perempuan, dan dikotomi status lainnya. Rakyat Indonesia tentu mengamini apa yang disajikan oleh iklan tersebut. Harapan pun membuncah. Biaya untuk anak sekolah bisa digunakan untuk biaya hidup lainnya yang semakin hari semakin berat.
Pada kenyataannya, situasi emosional yang tersaji dalam iklan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Situasi emosional itu berubah menjadi situasi penuh amarah dan ketidakpercayaan. Memang ada sekolah yang benar-benar gratis (tidak memungut uang ini itu), tetapi di sisi lain ada sekolah yang sangat mahal, bersembunyi di balik status sekolah. Seakan-akan iklan itu hanya untuk sekolah negeri yang biasa-biasa saja, namun bukan untuk sekolah negeri yang statusnya mengklaim sebagai sekolah plus. Klaim atas status tidak jarang menjadi alat dan alibi untuk menarik pembiayaan yang mahal, yang kadang di luar kalkulasi.
 Suasana kelas (Sumber: dok. pribadi)
Suasana kelas (Sumber: dok. pribadi)
Dapat dibayangkan untuk masuk SD favorit biaya lebih dari Rp 3 juta, untuk masuk SMP favorit di atas Rp 5 juta, apalagi masuk SMA favorit tentu di atas Rp 7 juta. Anehnya, yang antre banyak sehingga semakin menyuburkan kapitalisme pendidikan di negeri ini. Kondisi ini tentu bertentangan dengan konsep sekolah untuk semua. Iklan sekolah gratis itu juga seakan tidak punya pengaruh apa-apa.
Sebagian besar orang tua siswa berasumsi, gratis itu berarti tanpa membayar apapun. Asumsi itu wajar karena sebagian besar orang tua sudah termakan iklan sekolah gratis. Bahkan, banyak orang tua mengeluh ketika dimintai biaya untuk pengadaan buku atau sumber belajar lainnya meski itu menjadi hak milik anaknya.
Kesenjangan apa yang disajikan di iklan dan di lapangan disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap. Mispersepsi ini berpotensi pada sikap apriori masyarakat terhadap dunia pendidikan. Mestinya yang dimaksud gratis tersebut dijabarkan dengan jelas sehingga informasinya tidak terpotong-potong. Apakah gratis pendaftarannya, gratis SPP-nya, gratis uang gedungnya, atau gratis uang pengembangannya? Semua harus dijelaskan.
 Potret siswa (Sumber: dok. pribadi)
Potret siswa (Sumber: dok. pribadi)
Polemik sekolah gratis akan semakin parah jika penyelenggara pendidikan dan guru tidak ikhlas menerima kebijakan tersebut. Jangan sampai guru bertindak kapitalis dengan bisnis LKS atau barang lainnya kepada siswa karena program sekolah gratis mengurangi pendapatannya dari sekolah di luar gaji resmi.
Polemik sekolah gratis akan terus berlangsung jika pemerintah tidak mengontrol pelaksanaan UU Badan Hukum Pendidikan secara ketat dan memberi pencerahan kepada penyelenggara pendidikan. Tidak itu saja, mekanisme sekolah gratis harus diinformasikan dengan jelas dan tentu ada hukuman bagi penyelenggara yang melanggar. Jika ini sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, barulah kita katakan: Sekolah Bisa! Semua pasti berharap terealisasinya pendidikan gratis. Agar anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan wajib 12 tahun dan dapat mengangkat martabat dan derajat bangsa kita.