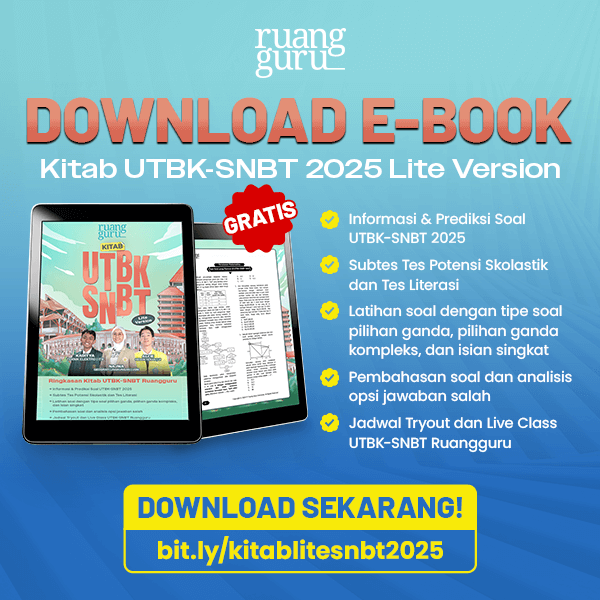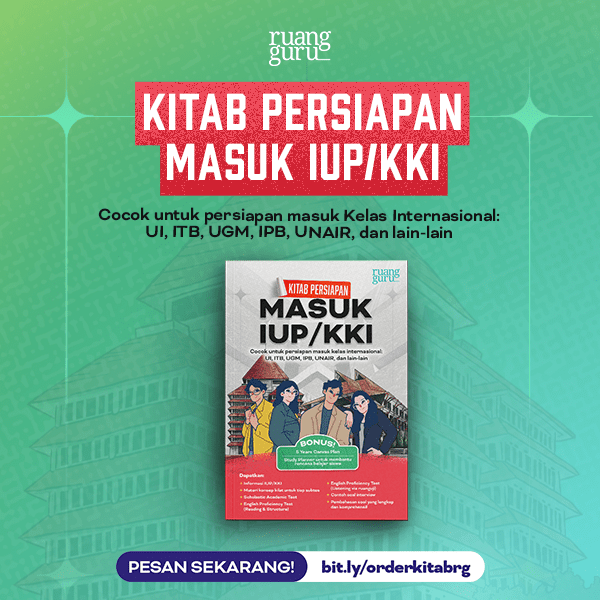Polaroid

Karya: Tsalaisye
—
Lelaki itu berjalan menunduk. Siapa pun yang melihatnya pasti akan mengira ia sedang menghitung jumlah batako yang dipijaknya. Kaki yang terbungkus sendal kulit usang itu sesekali berhenti. Barulah sampai di persimpangan, ia kemudian mengangkat kepalanya sembari menarik napas panjang. Dilihatnya langit yang mulai berwarna jingga. Lampu kendaraan mulai menyilaukan matanya. Sore itu, ia akan menanggalkan semuanya.
***
Hari sangat terik. Lelaki itu, Karya, berjalan mencari tempat yang sedikit teduh. Wajahnya terlihat kalut, kontras dengan orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang itu dihiasi oleh senyuman. Mereka saling tertawa dan bergurau. Sebagian besar di antara mereka saling bergantian memotret. Ada juga beberapa yang sedang asyik memotret dirinya sendiri.
“Neng, mau saya foto? Sepuluh ribu langsung jadi.” Kata Karya pada dua perempuan muda yang juga sedang berteduh di gazebo. Keduanya menggeleng. “Buat kenang-kenangan, Neng.” Mereka kembali menggeleng. Lalu dengan perlahan mereka berjalan menjauhi Karya. Entah karena risih atau memang mereka akan melanjutkan tamasya berkeliling melihat miniatur Indonesia. Karya tak tahu. Mungkin lebih tepatnya, ia tak lagi mencari jawaban itu. Karena kejadian serupa ini sudah makanannya sehari-hari. Bahkan sudah berbulan-bulan hingga bertahun-tahun terakhir.
Karya duduk di kursi melingkar yang terbuat dari semen yang dicat warna hijau muda di bawah gazebo. Diraih botol air mineral yang berada di dalam tas. Ia buka tutupnya dan meminum isinya. Di kejauhan Karya melihat deretan pepohonan yang terkena angin. Ia teringat kembali percakapan dengan istrinya.
“Mas, kata si Atik, bisa kok kamu ikut dengan suaminya. Ada yang pulang kampung satu orang, jadi ya bisalah Mas menggantikan orang itu.”
“Oh iya? berapa gajinya?”
“Tiga juta, Mas. Nanti kalau ada lebihan sapi bisa ada bonus katanya. Lumayan kan?”
“Iya, nanti Mas pikir-pikir dulu.”
“Jangan kelamaan mikirnya, nanti keburu disamber orang lain.”
Karya ingat, sudah berkali-kali istrinya membantunya mencari pekerjaan baru. Dari menjadi kurir paket, ojek online, hingga penjaga toko. Tetapi Karya tak bergeming. Ia menganggapnya angin lalu. Baru kali ini, Karya mulai goyah. Ditutupnya kembali botol air mineral itu. Lalu ia masukkan kembali ke dalam tas. Dirabanya, kamera yang kini berada di pangkuannya. Pikiran Karya kembali melayang ke masa lalu. Dahulu kamera itu pernah menjadi primadona.
Setiap kali Karya berkeliling, semua mata tertuju padanya. Kemeja dan rambut yang ia tata rapi lengkap dengan topi dengan warna senada itu terlihat sangat keren bagi orang-orang. Kamera yang bergelantungan di dadanya itu memang selalu menarik perhatian, terutama anak-anak. Mereka merengek pada ibunya meminta dipotret. Dan tentunya rengekan itu tidak membuat ibunya menurut, paling-paling yang didapati anak itu hanya pukulan di pantat atau jeweran di telinga karena terus merengek meminta uang untuk bisa difoto oleh Karya.
Tidak sembarang orang bisa memakai jasa Karya. Hanya orang kelas menengah ke atas saja yang mampu membayarnya. Kecuali untuk acara besar seperti ulang tahun, sunatan, maupun kawinan. Biasanya mereka memanggil Karya untuk mengabadikan momen itu. Ia dan istrinya bahkan sibuk menata jadwal memotret. Tetapi itu dulu, kalo sekarang, lelaki itu harus berkeliling di tempat wisata dan seringkali pulang tanpa memotret apapun. Kini ia merasa harus mencoba pilihan yang dibuat oleh istrinya.
“Ngelamun aja, Bang” suara Darto mengagetkan Karya. Di lehernya melingkar sebuah tali dari kamera butut warna hitam.
“Ah tidak, biasalah rehat dulu. Panas.” Jawab Karya dengan senyum tipis.
“Iya emang panas sekali. Oh iya, Bang. Bang Pani pamitan tuh. Tadi sih sudah nggak bawa kamera. Bang Karya sudah ketemu belum?”
“Belum. Di mana dia?”
“Tadi di Warung Mak Siti, traktir kopi, Biasalah.”
“Sebenarnya aku juga mungkin akan menyusul Bang Pani. Pamitan.”
“Ah jangan bercanda, Bang. Saya lebih dari tahu kalau memotret dan Bang Karya itu tidak bisa dipisahkan. Karya si Tukang Poto.”
“Tapi kalau begini terus, bisa keteteran bayar kuliah anak.”
“Emangnya mau kerja di mana lagi, Bang? Umur udah mau lima puluh gitu?”
“Tukang potong daging sapi.”
“Ah, Bang Karya ini sukanya bercanda.”
“Sejak kapan saya suka bercanda, to.”
“Tangan Abang yang lembut ini nggak mungkin cocok sama pisau. Sudah ah jangan bercanda. ”
“Sudah kubilang aku tidak bercanda.”
Darto menatap mata Karya. Tawa yang tadinya selalu ada di suaranya mulai menghilang. Darto menyadari apa yang sedang dirasakan lelaki yang sudah dianggap sebagai kakaknya itu. Ia kemudian menepuk bahu Karya. Keduanya sama-sama tahu perpisahan antarmereka pasti lambat laun akan terjadi. Bukan cuma bagi Karya dan Darto, tapi bagi seluruh paguyuban jasa foto polaroid di tempat wisata itu.
Satu per satu dari mereka pindah ke profesi lain yang dianggap lebih menguntungkan dan lebih stabil secara ekonomi. Jika beruntung, beberapa di antara mereka bekerja di sebuah studio foto. Jika tidak, paling mentok mereka hanya menjadi tukang ojek online. Untuk bersaing dengan juru foto yang kekinian pun mereka merasa tidak akan mampu. Kedua lelaki itu, kini hanya duduk berpaku dengan lamunannya masing-masing. Masa depan yang serba tidak pasti.
Baca Juga: Cerpen Keluarga yang Menangis Pada Dini Hari Karya Edy Firmansyah
Karya membuka mata. Cahaya sudah menembus jendela kamar yang kain tirainya mulai menipis. Di beberapa bagian tirai terdapat robekan dan bolongan. Cahaya menjadi lebih terang melewati robekan dan bolongan itu. Silau. Tidur di sore hari memang membuat linglung. Sejenak Karya berpikir saat itu pagi hari. Cahaya yang menembus celah-celah jendela terasa hangat. Kemudian ia ingat, saat ini sudah sore. Ia mencoba menggerakkan sedikit tubuhnya dan kemudian segera beranjak.
Ningrum, istri Karya sedang duduk di ruang tamu. Selain sebagai ruang tamu tempat itu juga sekaligus menjadi ruang tengah dan ruang televisi. Ruangan itu hanya berjarak dua sampai tiga langkah dari kamar tidur. Ningrum memakai baju berwarna kuning bermotif bunga berwarna ungu dan daun berwarna hijau. Karya memandangi istrinya yang menatap televisi dengan tawa di wajahnya.
Acara televisi sore itu menampilkan adegan orang terjatuh. Di bagian bawah layar bertuliskan ‘Kejadian Lucu dan Tak Terduga di Atas Panggung’. Seringkali musibah menjadi lelucon sampai disiarkan di televisi, pikir Karya keheranan. Ia memperhatikan kembali istrinya, beberapa helai rambut berwarna hitam jatuh di dahi, dan sisanya dikuncir sekenanya ke belakang. Karya duduk persis di samping istrinya. Si istri langsung tersadar akan kehadiran suaminya.
“Bagaimana jadi, Mas? Berangkat jam berapa?” Ia bertanya dengan sisa tawa yang belum tuntas.
“Tidak tahu nanti.” Jawab Karya sembari menghela napas.
“Nah loh kok malah nggak tahu ini gimana? Jangan bilang mas masih ragu.” Tawa istrinya sudah benar-benar hilang.
Bukannya menjawab. Karya justru meraih kamera polaroid yang tertata rapi di meja. Di meja itu berjajar pula film-film yang sudah dikumpulkan Karya. Ia menyentuh kamera itu perlahan. Tiba-tiba saja Karya ingat Ismanto. Teman SMA-nya yang pertama kali mengajarkan dia menggunakan kamera.
Setelah mahir memotret, barulah Karya memutuskan untuk membeli kamera ini dengan tabungannya. Sejak saat itu, dirinya dan kamera itu tidak dapat terpisahkan. Semua orang pun memanggilnya Karya si Tukang Poto. Kamera ini juga yang mempertemukan dirinya dengan Ningrum. Ia memotret keluarga Ningrum di acara sunatan dahulu.
Saat menjadi tukang foto, Karya memang sering melihat rupa-rupa senyum. Tetapi di hari itu, Karya melihat lengkungan senyum yang paling indah. Senyum Ningrum. Sepulang dari memotret, ia tak bisa melupakan gadis itu. Sekarang Ningrum yang memiliki lengkungan senyum paling indah itu menjadi istrinya berkat kamera polaroid itu.
“Tidak kok! Sudah tidak ragu lagi.”
“Gitu dong, lagian apalagi yang mau diharapkan jadi tukang foto, sekarang tuh orang-orang sudah pada bisa selfi sendiri. Mending jual saja tuh kamera. Bisa buat beli buku pelajaran si Dewi anak kita. Buku-buku sekarang makin mahal. Ya kan?”
“Iya-iya.”
“Jadi berangkat kapan? ”
“Habis ini setelah mandi.” Karya beranjak dan meraih handuk berwarna merah. Di lingkarkan handuk itu di lehernya.
Baca Juga: Cerpen Masih Ada Waktu Karya Eko Triono
Lelaki itu sampai di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas masih berwarna hijau. Ia terhenti menunggu lampu berubah menjadi merah. Di seberang jalan ia melihat toko kecil tempat tujuannya. Wajahnya sudah tidak lagi tertunduk. Barangkali ia sudah selesai menghitung batako. Wajahnya kini menatap lurus ke arah toko bertuliskan “Jual-beli Barang Bekas” yang menjadi tujuannya itu.
Lampu merah menyala. Lelaki itu bergegas menyebrang jalan. Sekali lagi ia menyentuh tas berisi polaroid miliknya. Ia siap meninggalkan dirinya di toko itu. Ia yakin akan terlahir kembali meski dengan komposisi yang tidak utuh. Ia akan terlahir kembali menjadi orang yang berbeda. Karya si Tukang Potong Daging.
Tentang Penulis:
Tsalaisye, lahir pada 29 Maret 1994. Lulusan S-1 Sastra Indonesia UNY. Saat ini bekerja di bidang Bahasa dan Sastra sambil sesekali melirik jendela mencari inspirasi menulis. Dapat dihubungi melalui surel: tsalaisyenf@gmail.com, atau Instagram: @tsalaisyenf.
—
Ruangguru membuka kesempatan untuk kamu yang suka menulis cerpen dan resensi buku untuk diterbitkan di ruangbaca, lho! Setiap minggunya, akan ada karya cerpen dan resensi buku yang dipublikasikan. Kamu bisa baca karya cerpen menarik lainnya di sini, ya. Yuk, kirimkan karyamu juga! Simak syarat dan ketentuannya di artikel ini. Kami tunggu ya~
![[AB] Web Side Banner - Blog RG](https://cdn-web-2.ruangguru.com/landing-pages/assets/399009fa-feaf-4b6c-8321-92409d53a26a.png)