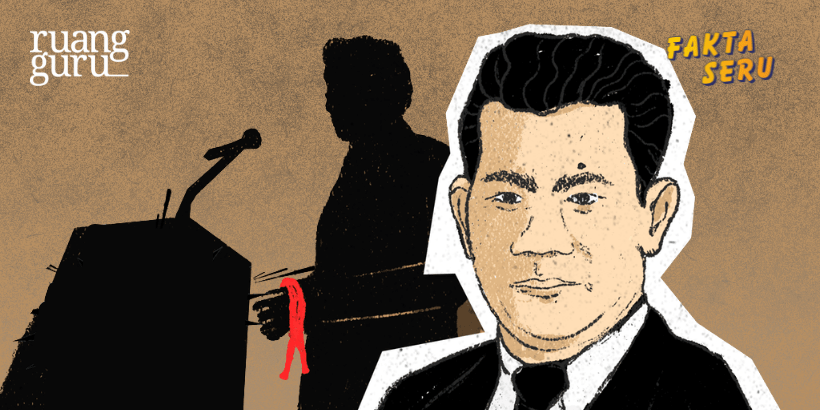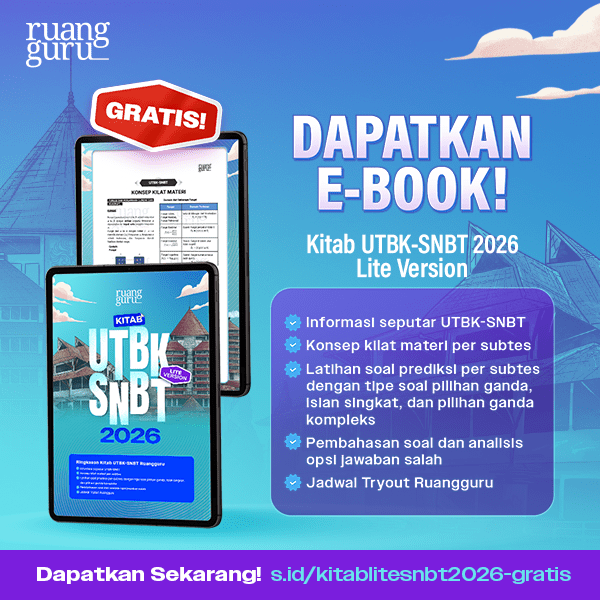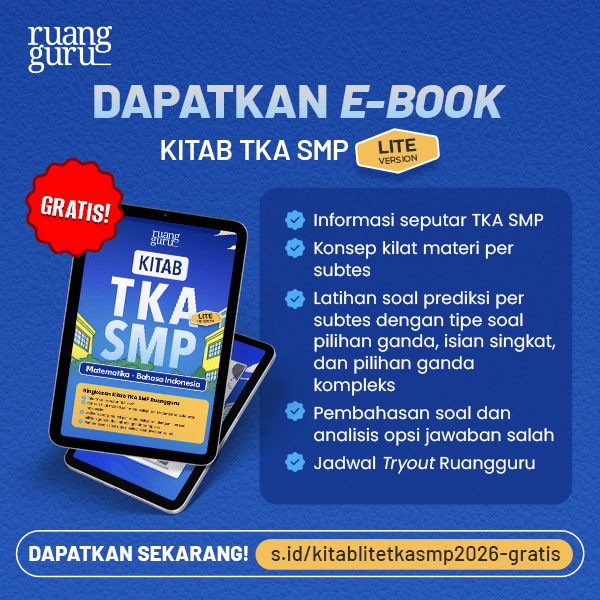Kisah Pendek dan Tragedi Panjang dalam Sumur

Sumur, karya Eka Kurniawan menceritakan tentang dampak perubahan iklim terhadap umat manusia. Bagi kamu yang penasaran dan tertarik membaca, berikut review selengkapnya!
—
Hal pertama yang ditangkap seorang pembaca dari sebuah buku adalah judul. Dan, hal pertama yang ditatap seorang pembaca dari sebuah buku adalah sampul. Kedual hal itu akan memberi kesan tertentu pada pembaca perihal isi sebuah buku. Begitu pula yang saya temukan pada buku mungil asuhan Eka Kurniawan ini. Pertama kali membaca judul dan menatap sampulnya saat pra pesan diumumkan, saya segera menebak bahwa kali ini Eka akan bercerita perihal tragedi (lagi).
Sebuah sumur di tengah hutan, pohon-pohon ranggas, pegunungan padas, nuansa langit kelam, serta dua orang yang berhadap-hadapan—ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi, pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas, bahwa ini bukan cerita bahagia. Dan saya meyakini satu hal: nanti, akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Apakah tebakan saya terbukti?
Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horror macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana: hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka akan menulis sebuah cerita horor, rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara sepasang anak kecil yang bertetangga desa, yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toyib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini.

Sebagai latar, dalam narasinya, Eka menerakan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia—bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan. Setidaknya itu dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toyib. Kota membuat Siti terjebak dan harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toyib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota.
Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikitpun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya, kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toyib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk.
Sepanjang membaca cerita ini, saya tersengal beberpa kali, seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Saya memaklumi ini, mengingat wadah cerita ini adalah cerita pendek. Cerita masa kecil Toyib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alenia pendek pada halaman pertama, plot berganti pada alenia kedua, perihal perseteruan ayah Toyib dan ayah siti, yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka.
Plot terus berjalan, kejar-mengejar, menerakan kisah hidup Toyib dan Siti yang seolah buntu, kematian orang-orang di sekitar, memunculkan tragedi-tragedi baru, hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toyib dan suami Siti, yang belakangan, keduanya ditemukan di dasar sumur itu. Tanpa nyawa dan tanpa catatan (hal. 47).
Baca Juga: Resensi Buku Kosmos Karya Carl Sagan
Kata ‘tanpa catatan’ seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu, atau apa motif istri Toyib pergi ke sumur itu, semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja, Toyib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka. Pembaca bebas mengungkap apa-apa yang tak terugkap dalam Sumur Eka ini dengan versi masing-masing. Dan terlepas dari itu semua, tebakan saya akhirnya terjawab sudah: harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
Saya mengempas napas panjang di pungkasan cerita, sebuah tragedi panjang dalam kisah pendek. Benar-benar pendek. Untuk menamatkan buku ini saya hanya butuh waktu 25 menit. Dalam dalam jangka waktu tersebut, mungkin dimulai sekitar menit kedua—saat ayah Toyib mengakhiri hidup ayah Siti—sampai kalimat terakhir yang menutup cerita ini, saya terus-terusan didera perasaan sebak. Sebak pada penderitaan tokoh-tokohnya yang tak berkesudahan. Sebak pada kenaifan mereka. Pada satu sisi, cerita ini tak jauh dari novel-novel Hamka terutama perihal kasih tak sampai yang dikorek secara terus menerus hingga memunculkan efek luka tertentu pada benak pembaca.***
Tentang Peresensi:
Mashdar Zainal lahir di Madiun 5 Juni 1984, penyuka puisi dan prosa. Tulisannya tersiar di beberapa media cetak maupun daring. Telah menerbitkan beberapa novel dan buku kumpulan cerpen. Salah satu novelnya: ‘Kartamani, Riwayat Gelap dari Bonggol Pohon’, Penerbit Basabasi, 2020. Kini bermukim di Malang.
—
Ruangguru membuka kesempatan untuk kamu yang suka menulis cerpen dan resensi buku untuk diterbitkan di ruangbaca, lho! Setiap minggunya, akan ada 1 cerpen dan 1 resensi buku yang dipublikasikan. Yuk, kirimkan karyamu sebanyak-banyaknya! Simak syarat dan ketentuannya di artikel ini. Kami tunggu ya~